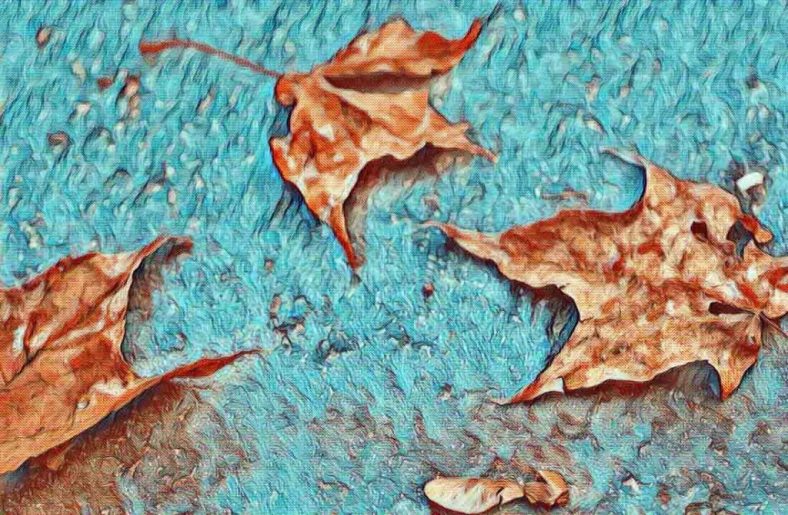Tak ada orang lain yang bisa mengantikan posisi Musri untuk bisa menyampaikan kematian. Mendengar suaranya, semua orang seperti lupa sedang berduka. Orang-orang lebih tenang menghadapi nasib buruk dan mereka tak akan mau melihat masa lalu.
Pernah ada yang mencoba untuk mengantikan Musri ketika rinai hujan yang deras menerjang sepanjang sore. Musri masih berada di sawah dan harus membetulkan saluran air yang pecah karena tergerus air hujan. Itu pun karena terpaksa, Musri belum bisa kembali ke masjid untuk bisa mengabarkan kematian Wak Paino yang sudah sakit menahun dan menghembuskan nafas terakhirnya.
“Innalillahi wa innailaihirojiun…..Innalillahi wa innailaihirojiun. Telah meninggalkan kita bersama Wak Paino, warga RT 2 RW 1. Jenazah akan dikuburkan pukul 21.00 WIB.”
Selesai Kusno mengabarkan berita kematian itu, ratusan warga berbondong-bondong untuk ke masjid dengan suara tangis yang tak tertahan. Mereka menerjang hujan dan meratapi kematian Wak Paino yang dikenalnya sebagai petani yang jujur. Kesedihan itu menutupi senja yang kemerahan.
Seisi kampung itu mulai banjir air hujan yang bercampur dengan air mata para warga. Senyum Wak Paino seperti melayang di angkasa sambil menari salsa. Mengitari seluruh sudut perkampungan dengan lincahnya. Bahkan sampai jenazah itu dikebumikan, para warga masih saja menangis. Keluarga Wak Paino juga terus meratap, membayangkan dirinya masih hidup dan berada di sekeliling keluarga tercinta.
Kesedihan itu belum juga berhenti sampai di penghujung malam, beberapa warga sudah mulai gaduh. Mata mereka tak ada yang terpejam. Penderitaan sepertinya sulit untuk dihilangkan. Berharap merangkai senyuman seperti menunggu tetesan hujan di musim kemarau panjang. Mereka menyalahkan Kusno yang berani-beraninya mengantikan peran Musri sebagai penyampai kabar kematian.
“Siapa yang suruh si Kusno?” semua warga terdiam.
“Ini sudah jelas salah Kusno, kita ini sudah lelah bekerja. Harus ditambahi kesedihan seperti ini. Apakah mereka lupa, kalau kabar kematian itu seperti menusuk perutmu dengan senjata tajam yang tak terlihat.”
Semua warga bersepakat, mereka meneken perjanjian di atas kertas putih yang dibubuhi materai kalau hanya Musri yang boleh menyampaikan kabar duka dari masjid-masjid. Mereka tak mau lagi larut lagi dalam kesedihan. Apalagi kabar-kabar kematian kini hampir tiap hari berdatangan.
Sejak saat itu, Musri dibebastugaskan oleh warga di desa dari pekerjaaanya sebagai buruh tani. Mereka patungan untuk bisa membayar gaji Musri tiap bulan. Ia hanya diberikan tugas setiap hari untuk menjadi tukang penyampai kabar kematian dari mikrofon masjid yang membahana.
Selepas Subuh, saat matahari belum terlihat hadir dan suara burung kutilang yang bersahutan menemani udara dingin yang terus saja menyergap. Musri tidak beranjak dari peraduannya, duduk bersila di barisan kedua setelah selesai Salat Subuh berjamaah. Sarung kotak-kotak yang dipadu dengan gamis berwarna coklat melekat dalam kulitnya yang kian langsat.
Segera ia berdiri dan berjalan pelan menuju mikrofon yang ada di sisi mimbar. Kedua matanya menatap erat dan suara yang benar-benar ditahan untuk bisa mengalun dalam hantaran udara. Ketika keluar, suaranya begitu terdengar dalam menyebut nama warga yang meninggal. “Pada hari ini, Bapak Sutrisno meninggalkan kita semua. Warga RT 1 RW 1 di Dusun Kuncir ini dikenal dengan sikap dermawannya dan pecinta burung tekukur. Kabar ini memang berat, tapi kehidupan hanya persinggahan. Semua pasti akan pergi dan hanya meninggalkan jejak amalan baik yang tak pernah surut.”
“Kau dengar, suara Musri begitu tenang. Mereka yang meninggal pasti lebih tenang ketika dikabarkan seperti itu.” kata-kata itu muncul dari warga desa yang demikian adem ketika mendengar Musri menyampaikan kabar kematian.
“Kami semua pun tak akan takut mati kalau Musri masih ada dan membacakan nama kami semua.”
Semua orang mati menimbulkan kesedihan, tapi Musri hadir dengan kata yang berbeda untuk menenangkan tangis. Semua harus bisa merelakan, semua warga harus bisa terus bekerja. Tidak boleh larut dalam kesedihan yang mendalam dan meratapinya tanpa ada ujung. Mengirimkan mereka dalam ruang kesedihan yang tak juga surut. Bukankan kehidupan di dunia memang sementara, dan riang senyuman itu akan abadi di angkasa.
Selepas menguburkan jenazah Sutrisno, para warga kembali ke pematang. Mereka tetap bisa menanam padi dan singkong dengan sesekali melemparkan tembang. Berbicara tentang harapan dan sisa panen yang bisa dipakai untuk bertahan hidup. Menghabiskan hari di pematang dengan berseri tanpa beban yang merintangi.
Saat matahari masih sepenggalah, suara pelantang masjid kembali terdengar. Para warga menghentikan sejenak aktifitasnya di ladang, mereka mencari tempat berteduh. Meminum air putih dan menghentikan kegiatannya di sawah untuk mendengarkan suara dari Musri yang mulai terdengar sayup di telinga.
“Siang ini, salah satu putra terbaik di desa kita, Ikhsan telah meninggalkan kita semua. Dalam usianya yang masih muda, Ikhsan telah dengan gigih menentukan arah dan cita-citanya. Meskipun dalam perjalanan itu ia akhirnya menemui kematian. Tapi bukan itu yang dituju, perjalanan dan proses Ikhsan akan terus meresap dalam diri kita. Ikhsan meninggal dalam senyum ketika dunia ini merengut nyawanya.” seluruh warga terdiam dan khusuk mendengarkan.
“Iksan memang belum genap 30 tahun usianya, tapi sejak muda ia adalah demonstran. Sudah banyak orang yang korupsi menyumpahinya untuk segera mati, biar suara-suara kritisnya ikut lenyap. Sumpah serapah itu tak mempan sepertinya, putra terbaik dari desa kita baru meninggal ketika sebuah becak yang dinaikinya diseruduk truk pengangkut semen pagi tadi.”
Masyarakat desa tegar mendengar kabar itu. Mereka memukul dadanya dan menunjukan peluh yang dilakukan anak-anak muda untuk terus berteriak kalau memang ada ketidakadilan. Teriakan itu biar sampai di telinga para koruptor, membuat tidur mereka tak nyenyak dan memastikan tangan-tangan mereka akan dipotong oleh rakyatnya sendiri di alam baka.
Dan itu harus terus dirawat, para warga yakin masih banyak anak-anak muda lain yang pasti meneruskan jejak Ikhsan. Dan jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Membunuh satu hanya akan menambah ribuan lainnya untuk ikut berteriak.
Pada sebuah petang, ketika Musri baru saja terpejam di ranjangnya yang hangat, pintu rumahnya digedok dengan keras. Suara yang membuyarkan mimpi indahnya mengendarai sepeda motor bermesin besar di atas perbukitan yang hijau. Segera saja ia bangkit dan membuka pintu dengan mata yang masih lengket di selimut mimpi. Pandangannya masih separoh dan kedip matanya yang tak kuat menahan kantuk.
“Ada apa?”
“Ditunggu Pak Modin, ada yang meninggal.”
“Siapa?”
“Pak Drajat dan Pak Wiryo.”
“Alamatnya mana mereka dan kenapa meninggalnya?”
“Pak Drajat meninggal karena serangan jantung, alamatnya di RT 2 RW 3 nomor 56. Dia orang terhormat, wakil rakyat yang rumahnya paling besar di dekat jalan raya, orang termasyhur yang sering bagi-bagi duit saat pemilu.
“Orang yang katanya uangnya tak ada serinya itu ya?”
“Iya, tembok rumahnya katanya berisi uang. Kenapa orang kaya dan suka bagi-bagi uang seperti itu harus mati. Apakah kematian tak bisa memilih orang yang pantas untuk dicabut nyawanya.”
“Tanya malaikat saja.” Musri sudah mulai kesal mendengar jawaban itu.
“Satunya lagi siapa yang meninggal?”
“Pak Wiryo. Bramacorah tulen kalau yang ini. Tadi meninggal karena dibakar massa, katanya habis mencuri sapi di desa sebelah. Alamatnya di RT 5 RW 1 nomor rumahnya 21.”
Musri langsung bersiap. Ia mencuci muka dan berharap sisa-sisa mimpi segera pergi. Seluruh masyarakat di desa jelas menunggu suara dan kabar darinya. Gamis putih diraihnya di ujung tembok, pada sebuah paku besar yang menancap di dinding. Dan sarung kota-kotak berwarna biru yang tadi sempat dipakai selimut tidur langsung disahut. Peci hitam yang sudah kusam menutupi rambutnya yang belum sempat disisir.
Ia berjalan cepat menyusuri jalanan desa. Malam yang penuh dengan hamparan bintang-bintang menemani perjalanannya dalam gulita di kampung yang memang minim lampu penerangan. Pandangannya lurus ke depan, melihat beberapa remang cahaya serta daya ingatnya yang berloncatan. Ia harus segera mengabarkan dua orang yang meninggal malam ini juga. Karena nanti sebelum Subuh dua jenazah itu harus segera dikuburkan.
Langkahnya semakin cepat, berkejaran dengan kunang-kunang yang malam itu menemaninya. Memberikan sedikit cahaya dalam jalanan yang semakin gulita. Kunang-kunang itu pun semakin banyak, apakah karena semakin banyak orang mati dan kuku-kuku mereka yang kini berterbangan di berbagai jalan desa.
Saat tiba di masjid, lima orang sudah menunggu di halaman. Mereka juga mempersiapkan alat-alat untuk memandikan jenazah. Dari kelima orang itu, tak ada yang berani untuk memegang mikrofon di masjid. Mereka sadar tugas itu hanya Musri yang diberikan kewenangan dengan suara emasnya yang bisa mendinginkan emosi dan ingatan tentang kesedihan.
“Kenapa lama sekali?” tanya mereka pada Musri yang baru saja melepas sandal di teras Masjid.
“Tertidur, masih ngantuk. Kau pikir jam segini bukan enak-enaknya kita memeluk bantal.”
“Cepat dikabarkan, jenazah sudah mau dimandikan.”
Musri mengambil air wudhu. Matanya benar-benar lengket dan tak mampu memandang lampu-lampu yang benderang di dalam masjid. Ia kini lebih segar, wajahnya lebih bercahaya setelah disiram air wudhu. Pandangannya terarah dan pikirannya kembali melayang pada dua nama jenazah yang akan disampaikan kabar dukanya.
Langkahnya agak mengigil ketika kakinya mulai merayap di lantai-lantai yang begitu dingin. Angin masih sepoi menelan malam yang larut dalam dekapan. Langkahnya lebih ringan ketika deretan karpet yang membentang memberikan sedikit kehangatan buat permukaan kakinya.
Satu nafas ditarik lebih dalam, ia mencoba untuk mengatur nada suaranya tetap tegas dan bersahaja meskipun dikepung dinginnya malam. Kumpulan nafas itu pun terbentuk sempurna ketika tangan kanannya mulai meraih sebuah mikrofon dengan wibawa. Kantuk masih menyergapnya dan fokus kepalanya yang tak lagi terarah.
“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Innalillahi wa innailaihirojiun. Kabar duka bagi kita semua, malam ini, salah satu orang terhormat di kampung kita, Bapak Drajat telah meninggal dunia. Wakil kita yang terhormat di gedung rakyat telah tertangkap warga di kampung sebelah mencuri sapi. Wajahnya dikenali dan dicurigai oleh warga yang melihatnya berkali-kali mencuri sapi. Aksinya kali ini tertangkap langsung oleh warga dan menjadi penghujung kehidupannya. Mukanya babak belur, sulit dikenali lagi. Tangan kanannya patah dan kedua kakinya tak bisa berdiri sebelum nyawanya meregang. Semoga semua amal ibadahnya diterima disisinya dan kita semua bisa memaafkan dosa-dosa almarhum.”
“Innalillahi wa innailaihirojiun. Malam ini juga kita harus rela kehilangan saudara terbaik kita, Bapak Wiryo, warga RT 5 RW 1 nomor 21 yang meninggal karena serangan jantung. Kehidupannya yang keras untuk memperjuangkan keluarganya dari kemiskinan menjadikan almarhum terus berjuang sampai serangan jantung menghentikan langkahnya. Keteladanan beliau memberikan kita semua inspirasi kalau kehidupan harus diperjuangkan dan saling berbagi. Semoga kita semua bisa memberikan doa dan keikhlasan dari semua warga untuk melepas jenazahnya ke surga.”
Para warga mulai keluar rumah. Mereka bersiap untuk mensalatkan jenazah. Dalam perjalanan menuju ke masjid, mereka saling berbisik,”Bangsat, berarti uang kemarin dari Pak Drajat saat mau coblosan dari hasil mencuri sapi.”
Karya : Aan Haryono
Tinggal di Surabaya, Founder Pinus Story, Kelas Menulis di atas Gunung. Bukunya yang sudah terbit adalah Pagupon (2012).