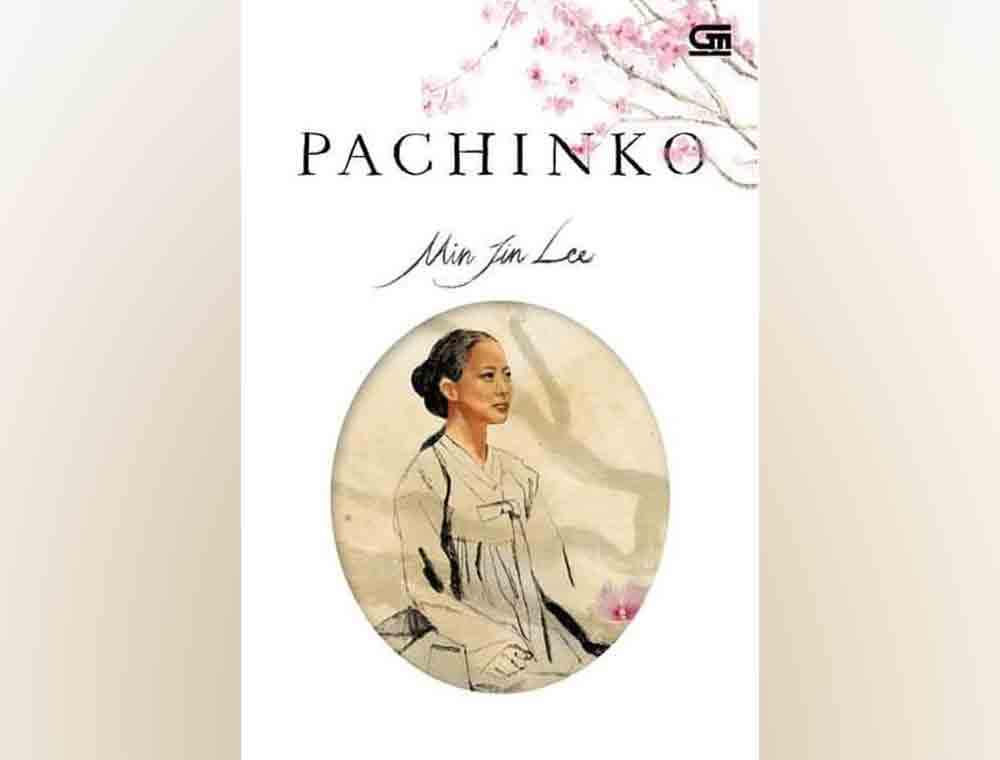Judul : Pachinko
Penulis : Min Jin Lee
Penerbit : Grand Central Publishing
Membaca Pachinko seperti membaca perempuan. Paling tidak itulah benang merah yang ingin disampaikan penulis. Menyiratkan bahwa kehidupan perempuan (sekitar tahun 1910 hingga 1990an) didominasi oleh penderitaan. Penderitaan dalam arti yang sesungguhnya.
Go-saeng, kaum perempuan ditakdirkan menderita, demikian ungkapan salah satu dialog yang sempat muncul di akhir halaman novel setebal 565 halaman ini. Beberapa karakter tangguh yang muncul, digambarkan “sempurna” oleh penulis Min Jin Lee. Bahkan dihampir semua karakter.
Padahal tokoh yang dimunculkan cukup banyak, namun masing-masing dideskripsikan gamblang oleh Lee. Penggambaran ini terutama tentu saja masih berkutat dengan penderitaan. Tokoh yang dimunculkan oleh penulis berseliweran cukup ramai bak cameo.
Sebagian besar adalah perempuan tangguh yang masing-masing mencoba mengatasi deritanya dengan cara mereka sendiri. Meski tak menutup kemungkinan kemunculan tokoh pria (juga dengan karakter kuat) turut menggores warna tebal pada karya Lee kali ini.
Min Jin Lee adalah sosok penulis buku laris Free Food for Millionaires dan pernah menerima beasiswa dari New York Foundation for the Arts untuk kategori Fiksi, Peden Prize untuk Cerita Terbaik, serta Native Prize untuk Penulis Baru dan Berkembang.
Novel Pachinko ditulis Lee untuk menggambarkan para Zainichi, istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan orang Korea-Jepang yang menjadi migran dari zaman kolonial atau keturunan mereka. Sejumlah alasan menyebabkan mereka (kaum Korea) ini tak dapat kembali ke negara mereka hingga terpaksa menetap di Jepang dan tak bisa lagi menyaksikan tanah kelahiran Korea.
Keputusan untuk menjalani naturalisasi tidaklah mudah. Mereka kerapkali harus bergulat dengan sejarah panjang yang meresahkan serta diskriminasi hukum dan sosial yang menyesakkan. Barangkali ini menjadi salah satu sudut menarik yang coba digambarkan Lee terutama bagi kita pembaca awam yang tak mengenal bagaimana bertumbuhnya generasi ginseng di negara sakura.
Cerita dibuka dengan kehidupan sebuah keluarga kecil di pesisir pantai sebuah wilayah di Korea Selatan. Di Yeongdo, Busan, hiduplah seorang nelayan renta miskin yang cacat beserta istri dan anak perempuan semata wayangnya.
Mereka hidup dalam kondisi kekurangan, sehingga terpaksa harus menerima pemondok demi mendapatkan penghasilan tambahan. Sebagai pembaca awam, tentu saja narasi ini akan membawa kita pada sebuah kondisi yang memprihatinkan. Sebuah gambaran cerita tentang penderitaan. Dan memang dari sanalah semua bergulir.
Anak perempuan semata wayang, Sunja, yang dihamili oleh seorang pria, Hansu, (yang ternyata sudah berkeluarga dan tinggal di Jepang), turut menambah deretan ‘kesengsaraan’ yang coba dilukiskan. Kehamilan tanpa suami, jelas membawa aib bagi keluarga nelayan miskin itu.
Hingga Sunja terpaksa harus menerima pinangan dari seorang rohaniawan yang berutang budi pada keluarga nelayan itu karena telah menyelamatkan nyawanya. Alih-alih membalas budi, pendeta Baek Isak kemudian menikahi dan lantas membawa Sunja ke Jepang. Di sanalah semua konflik berawal.
Ternyata, Baek Isak tak berumur panjang di negara itu. Kematiannya akibat kekejaman sel penjara, membuat Sunja harus menghadapi kehidupan keras Jepang bersama anak semata wayangnya, Noa. Pertemuan kembali dengan Hansu, yang telah lama “hilang” dari kehidupan Sunja, juga turut menambah pelik alur cerita hidup Pachinko.
Meski disajikan dengan rentang waktu peristiwa yang cukup panjang (80 tahun), dengan diselingi kemunculan beragam karakter selama empat generasi yang silih berganti, Pachinko tak membosankan untuk dinikmati.
Peristiwa demi peristiwa disajikan bergulir cepat oleh Lee, tanpa pembaca merasa jenuh mengikuti setiap narasi. Alur bergerak cepat hingga tanpa sadar, pembaca telah dibawa pada kondisi kehidupan lain dari sebuah tokoh yang berbeda.
Lee begitu halus menggiring cerita, memindah sudut pandang dan mewujudkan masing-masing karakter dengan begitu detail dan seksama. Gambaran diversifikasi emosi Sunja saat kepergian beruntun suaminya (Baek Isak), anak pertamanya (Noa), hingga ibunya (Yangjin), masing-masing dilukiskan Lee dengan sentuhan yang cerdik meski tetap konsisten berpegang pada benang merah cerita yaitu perjuangan dan ketangguhan perempuan saat dihadapkan pada problematika kematian.
Pada beberapa bab, pembaca sesekali juga dibawa pada keterkejutan plot cerita yang muncul secara tak terduga. Misalnya saat Noa (anak pertama Sunja) yang tiba-tiba dikabarkan bunuh diri. Sebuah keputusan yang samasekali tak disangka Sunja, selepas pertemuan mengharukan yang nyaris baik-baik saja antara keduanya. Atau pada alur cerita tentang sosok Haruki Totoyama yang ternyata mengalami disorientasi seksual.
Beberapa adegan sensual dideskripsikan detail oleh penulis, karena novel ini memang ditujukan untuk usia dewasa. Termasuk berbagai problematika yang dimunculkan, tak ubahnya seperti berkaca pada persoalan sehari-hari. Begitu nyata dan dekat dengan keseharian, namun kadang luput dari perhatian.
Perjuangan untuk bertahan hidup ditengah keterbatasan akibat kemiskinan dan latar belakang peperangan. Kerinduan pada kampung halaman dan tanah kelahiran yang tak terperikan. Diskriminasi dalam keseharian akibat perbedaan identitas etnis dan kebangsaan.
Upaya mengatasi penderitaan para perempuan yang dihadirkan bersisihan dengan realitas kematian. Kisah perbedaan pandangan hidup dan upaya untuk keras pada diri sendiri, mungkin akan memberi pembaca banyak pelajaran ketegaran.
Meski di beberapa bagian terdapat kesalahan ejaan dan penyebutan, namun Pachinko layak menjadi referensi bacaan bagi penyuka novel klasik berlatar belakang sejarah. Meski tak menutup kemungkinan, yang menyukai kisah drama percintaan kontemporer pun bisa memasukkan Pachinko dalam daftar bacaan.
Beberapa kesalahan penulisan mungkin terasa masih bisa dimaafkan. Hanya perlu berbekal ketelatenan untuk mengikuti kisah alur cerita yang cukup panjang, mencermati beragam karakter yang dihadirkan, maka membaca ‘penderitaan’ dalam Pachinko akan terasa lebih menyenangkan.